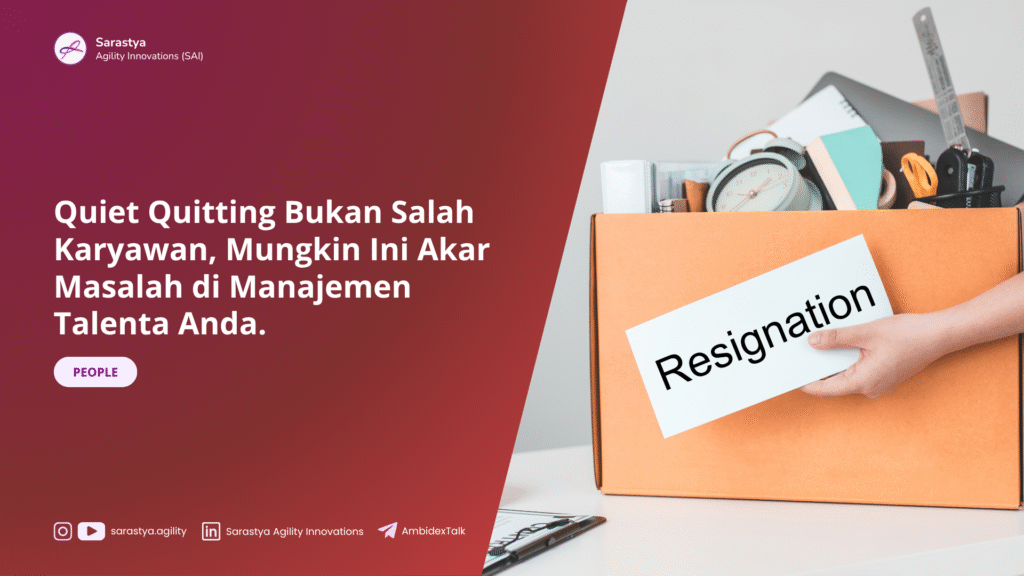Epidemi Senyap di Tempat Kerja
Belakangan ini, muncul kegelisahan yang dialami oleh praktisi HR/HC di beberapa organisasi yang merujuk pada istilah yang populer, yaitu “Quiet Quitting”. Fenomena ini dideskripsikan sebagai tindakan di mana karyawan tidak lagi bekerja melampaui deskripsi pekerjaannya. Mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu, menyelesaikan tugas minimum yang diminta, dan tidak lebih. Mereka secara mental dan emosional “mengundurkan diri” dari pekerjaan, meskipun secara fisik mereka masih hadir setiap hari.
Reaksi pertama dari banyak manajer dan pemilik bisnis yang saya temui adalah frustrasi dan kemarahan. Muncul berbagai label: “Gen-Z pemalas”, “generasi yang tidak punya etos kerja”, “karyawan tidak loyal”. Kita sibuk menyalahkan individu, mengadakan rapat-rapat darurat tentang cara meningkatkan engagement, dan mungkin berpikir untuk mengganti mereka yang dianggap “tidak bersemangat”.
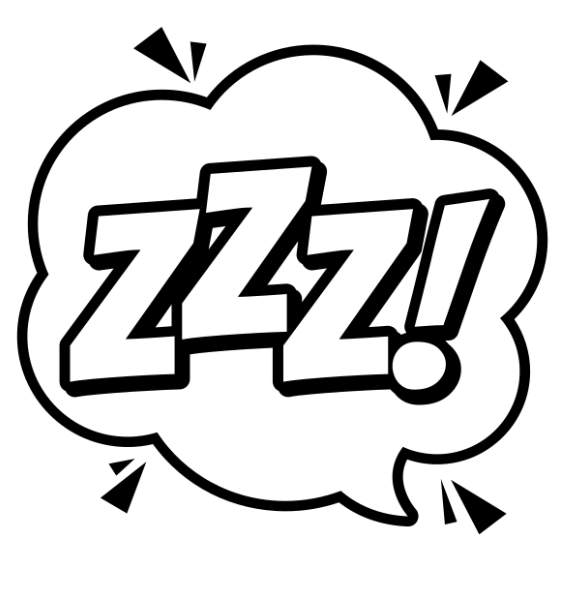
Namun, setelah mengamati fenomena ini dengan lebih dalam, saya justru sampai pada sebuah kesimpulan yang berbeda. Saya melihatnya bukan sebagai masalah kemalasan individu, melainkan sebagai sebuah gejala dari sistem yang lebih besar yang sedang sakit. Quiet quitting bukanlah penyakitnya; ia adalah demam yang menandakan adanya infeksi yang lebih dalam pada cara kita mengelola manusia. Menyalahkan karyawan karena melakukan quiet quitting sama seperti menyalahkan tanaman yang layu karena tidak mau tumbuh, tanpa pernah memeriksa kualitas tanah, air, dan cahaya matahari yang kita berikan.
Sebelum kita menunjuk jari pada karyawan, mari kita, para pemimpin, memiliki keberanian untuk menunjuk cermin pada diri kita sendiri dan sistem yang kita ciptakan. Mungkin, akar masalahnya ada pada “manajemen talenta” kita yang ternyata sudah usang dan tidak lagi relevan dengan zaman dan manusianya.
Membedah Fenomena ‘Quiet Quitting’, sebagai Sebuah Protes Pasif yang Rasional
Penting untuk kita luruskan pemahamannya di awal. Quiet quitting bukanlah tentang kemalasan. Kemalasan adalah ketika seseorang memiliki kesempatan dan sumber daya untuk melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, quiet quitting adalah sebuah penarikan diri yang sadar dan seringkali merupakan keputusan yang sangat rasional. Ini adalah tindakan di mana seorang karyawan berhenti memberikan aset mereka yang paling berharga dan tidak bisa dikontrak, yaitu “discretionary effort” atau upaya sukarela.
Upaya sukarela ini adalah energi ekstra yang diberikan karyawan di luar tugas minimumnya. Inilah gairah untuk memikirkan ide baru saat mandi, inilah inisiatif untuk membantu rekan kerja di departemen lain yang kesulitan, inilah kesediaan untuk tinggal 15 menit lebih lama untuk memastikan pekerjaan selesai dengan sempurna. Inilah “minyak” yang membuat mesin organisasi berjalan mulus. Ketika “minyak” ini ditarik, mesin mungkin masih berjalan, tetapi akan terdengar kasar, panas, dan rentan rusak.
Quiet quitting adalah bentuk protes yang sunyi dan pasif. Ini adalah cara seorang karyawan berkata, “Jika Anda hanya akan memperlakukan saya sebagai ‘sumber daya’ transaksional, maka saya akan memberikan kontribusi yang transaksional pula. Anda membayar saya untuk mengerjakan tugas A, B, dan C selama delapan jam. Baiklah, saya akan kerjakan persis A, B, dan C selama delapan jam. Tidak kurang, dan tentu saja, tidak lebih.”
Fenomena ini menjadi begitu masif belakangan ini, terutama di kalangan talenta muda (Milenial dan Gen-Z), karena adanya pergeseran ekspektasi fundamental. Generasi-generasi sebelumnya mungkin bisa menerima hubungan kerja yang murni transaksional demi stabilitas jangka panjang. Namun, generasi sekarang, yang dibesarkan di dunia yang lebih terhubung dan penuh pilihan, mencari lebih. Mereka mencari makna (purpose), pertumbuhan (growth), dan hubungan yang manusiawi (connection).
Ketika organisasi gagal menyediakan ketiga hal tersebut dan hanya menawarkan gaji sebagai kompensasi utama, maka karyawan pun akan merespons dengan hanya memberikan waktu dan tenaga mereka sebatas nilai gaji tersebut. Ini bukanlah pembangkangan; ini adalah sebuah keseimbangan baru yang mereka ciptakan sendiri dalam sebuah hubungan yang mereka anggap tidak seimbang.
Akar Masalah #1: Jebakan ‘Manajemen Sumber Daya’ yang Tidak Manusiawi
Akar masalah pertama terletak pada paradigma yang sudah mendarah daging di dunia korporat selama puluhan tahun, yaitu paradigma Human Resources Management (HRM) atau Human Capital Management (HCM). Perhatikan kata-katanya: Resources (Sumber Daya), Capital (Modal). Secara tidak sadar, kita telah terbiasa melihat manusia setara dengan aset lain seperti mesin, gedung, atau uang, sebagai sesuatu yang perlu dikelola, dioptimalkan, dan dieksploitasi untuk keuntungan perusahaan.
Paradigma ini termanifestasi dalam praktik sehari-hari. Deskripsi pekerjaan atau yang kita kenal dengan Jobdesc, seringkali hanya berisi daftar tugas dan tanggung jawab yang dingin dan kaku, tanpa menyentuh aspek aspirasi atau dampak. Penilaian kinerja fokus pada pencapaian KPI (Key Performance Indicators) numerik yang seringkali tidak menangkap kontribusi kualitatif seorang karyawan, seperti kemampuan mereka berkolaborasi atau membantu rekan setimnya. Hubungan antara atasan dan bawahan menjadi hubungan antara “pengawas” dan “pekerja”.
Dalam sistem seperti ini, karyawan secara alami akan merasa seperti “roda gerigi” dalam sebuah mesin besar. Mereka merasa bisa digantikan kapan saja. Mereka tidak merasa dilihat sebagai manusia utuh dengan segala harapan, impian, dan potensi uniknya. Mereka merasa menjadi “objek” manajemen, bukan “subjek” dari pertumbuhan.
Jadi, ketika sebuah organisasi yang beroperasi dengan paradigma “manusia sebagai sumber daya” ini kemudian menuntut karyawannya untuk “loyal”, “bersemangat”, dan “memberikan yang terbaik”, tuntutan itu terasa hampa, tidak tulus, dan bahkan munafik. Organisasi tidak bisa mengharapkan investasi emosional dari karyawannya jika organisasi itu sendiri hanya memberikan hubungan yang bersifat transaksional.
Quiet quitting adalah respons yang paling logis terhadap sistem yang sejak awal tidak melihat mereka lebih dari sekadar “sumber daya” yang bisa diukur produktivitasnya per jam. Jika saya hanya sumber daya, maka saya akan memberikan sumber daya saya (waktu dan tenaga) sesuai dengan apa yang dibayarkan, tidak lebih.
Akar Masalah #2: Ilusi ‘Jalur Karir’ dan Ketiadaan Pertumbuhan Nyata
Akar masalah kedua, yang sangat terkait erat dengan yang pertama, adalah ketiadaan jalur pertumbuhan yang nyata dan bermakna. Banyak perusahaan memiliki bagan “jalur karir” yang indah di dalam dokumen HR mereka, yang dipresentasikan dengan megah saat proses rekrutmen. Namun, dalam realitasnya, jalur tersebut seringkali hanya ilusi. Promosi terjadi sangat lambat, kesempatan untuk belajar hal baru sangat terbatas, dan pekerjaan sehari-hari menjadi monoton dan repetitif.
Knowledge worker modern, terutama dari generasi muda, memiliki “rasa lapar” yang luar biasa untuk bertumbuh. Motivasi utama mereka bukanlah stabilitas, melainkan penguasaan (mastery) dan kemajuan (progress). Mereka ingin merasa bahwa setiap tahun mereka menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka setahun yang lalu. Mereka ingin menguasai keterampilan baru, menghadapi tantangan baru, dan merasa bahwa kontribusi mereka semakin bernilai.
Ketika seorang talenta yang cerdas dan ambisius merasa bahwa pekerjaannya selama setahun terakhir tidak memberinya pertumbuhan apapun dan ia hanya mengulang pekerjaan yang sama berulang-kali dengan target yang sedikit lebih tinggi, maka “api” di dalam dirinya akan mulai padam. Ia akan mulai bertanya, “Untuk apa saya memberikan usaha ekstra? Toh tidak ada yang berubah. Tidak ada yang saya pelajari. Tidak ada tantangan baru.”
Baca Juga: Mengapa ‘Expert-Generalist’ Adalah Aset Paling Berharga dalam Tim Ambidex
Di sinilah quiet quitting dimulai. Bukan sebagai tindakan pembangkangan, tetapi sebagai mekanisme pertahanan diri yang logis. Ketika pertumbuhan eksternal (dari perusahaan) tidak tersedia, mereka akan mengalihkan energi dan semangat mereka ke pertumbuhan internal atau proyek di luar pekerjaan. Mereka berhenti berinvestasi secara emosional pada pekerjaan yang terasa seperti “jalan buntu”, dan mulai mengalokasikan energi premium mereka untuk hal lain yang memberikan mereka rasa kemajuan, entah itu kursus online, proyek sampingan, atau membangun jaringan profesional untuk pekerjaan berikutnya.
Quiet quitting dalam konteks ini adalah sinyal bahwa organisasi telah gagal memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar: kebutuhan untuk bertumbuh.
Generasi ‘Fearless’: Mengapa Gen-Z Tidak Takut untuk ‘Leave’
“Dulu, stabilitas adalah kemewahan. Sekarang, kebebasan adalah kemewahan.”
Fenomena quiet quitting ini menjadi semakin eksplosif karena kehadiran Generasi Z. Ada perbedaan psikologis fundamental antara Gen-Z dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka, pada umumnya, tidak terlalu takut untuk “Leave”, baik itu quiet quitting (pergi secara mental) maupun actual quitting (pergi secara fisik).
Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, secara pragmatis, mereka merasa masih muda dan melihat pasar kerja yang luas di mana banyak perusahaan terus menerus memerlukan karyawan baru. Mereka tidak merasa terikat pada satu perusahaan seumur hidup seperti generasi kakek-nenek mereka. Bagi mereka, loyalitas bukanlah kepada perusahaan, tetapi kepada pertumbuhan diri mereka sendiri.
Kedua, dan ini yang paling transformatif, adalah kemampuan mereka untuk bersolo karier dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seorang desainer grafis Gen-Z tidak lagi harus bergantung pada pekerjaan di sebuah agensi. Dengan laptop, koneksi internet, dan akun di platform seperti Instagram, Behance, atau Upwork, ia bisa membangun portofolionya sendiri, mendapatkan klien dari seluruh dunia, dan menjadi “perusahaan bagi dirinya sendiri”. Seorang pembuat konten, seorang pengembang aplikasi, seorang konsultan media sosial, teknologi telah mendemokratisasi akses untuk menjadi mandiri.
Ini menciptakan pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Dulu, perusahaan memegang kendali karena ia adalah satu-satunya sumber pendapatan dan stabilitas. Sekarang, bagi banyak talenta muda, perusahaan hanyalah salah satu opsi, bukan satu-satunya. Alternatifnya adalah kebebasan, otonomi, dan potensi penghasilan tak terbatas dari solo karier.
Oleh karena itu, ketika mereka dihadapkan pada lingkungan kerja yang tidak menumbuhkan, tidak bermakna, atau terlalu mengontrol, keputusan untuk “pergi” (baik secara mental maupun fisik) menjadi jauh lebih mudah. Ancaman kehilangan “stabilitas” tidak lagi semenakutkan dulu, karena kemewahan “kebebasan” kini berada dalam jangkauan. Ini memaksa perusahaan untuk secara fundamental mengubah proposisi nilainya: dari “kami memberimu pekerjaan” menjadi “kami memberimu tempat terbaik untuk bertumbuh”.
Beralih ke Paradigma Human Growth Management (HGM)
Jika quiet quitting adalah gejala dan manajemen talenta tradisional adalah penyakitnya, maka Human Growth Management (HGM) adalah obat dan vitaminnya. HGM adalah sebuah pergeseran paradigma fundamental yang secara langsung mengatasi semua akar masalah di atas. HGM tidak melihat manusia sebagai sumber daya yang perlu dikelola, melainkan sebagai potensi yang perlu ditumbuhkan.
Pendekatan ini mengubah segalanya. Peran pemimpin dan fungsi HR tidak lagi hanya tentang efisiensi dan kontrol, tetapi tentang menciptakan ekosistem di mana setiap individu bisa bertumbuh seutuhnya.
Baca Juga: Dari ‘Human Resources’ ke ‘Human Growth’, Roadmap Transformasi Fungsi HR Anda
Dari ‘Performance Appraisal’ ke ‘Growth Conversations’. HGM mengganti sesi penilaian kinerja tahunan yang terasa seperti “pengadilan” dengan “percakapan pertumbuhan” yang rutin dan berorientasi ke depan. Pertanyaannya bukan lagi “Apakah kamu mencapai target?”, melainkan “Apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya? Tantangan baru apa yang ingin kamu ambil? Bagaimana saya sebagai pemimpin bisa membantumu mencapai itu?”.
Dari Jalur Karir yang Kaku ke Jalur Pertumbuhan yang Fleksibel. HGM mengakui bahwa pertumbuhan tidak selalu harus vertikal. Ia bisa horizontal (mempelajari skill di departemen lain) atau mendalam (menjadi pakar di satu bidang). HGM fokus pada pembuatan ‘Individual Growth Plan’ yang disesuaikan dengan aspirasi setiap individu.
Dari Pekerjaan sebagai Tugas ke Pekerjaan sebagai Tujuan. HGM secara sadar menghubungkan pekerjaan sehari-hari individu dengan “Tujuan Mulia” organisasi. Ketika seorang karyawan tahu bahwa tugasnya yang “membosankan” sekalipun adalah bagian dari sebuah misi yang lebih besar, maka pekerjaan itu akan terasa lebih bermakna.
Pendekatan HGM ini secara langsung menjawab apa yang dicari oleh talenta modern dan menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan upaya sukarela dan investasi emosional mereka kepada organisasi.
Sebuah Panggilan Refleksi bagi Para Pemimpin
Fenomena quiet quitting bukanlah sebuah masalah karyawan yang harus diperbaiki. Ini adalah sebuah umpan balik yang sangat berharga bagi kita, para pemimpin. Ini adalah sinyal dari sistem kita bahwa cara kita mengelola manusia tidak lagi selaras dengan zaman dan tidak lagi memenuhi kebutuhan jiwa dari talenta-talenta terbaik kita.
Kita bisa memilih untuk mengabaikan sinyal ini, melabeli karyawan kita sebagai pemalas, dan terus berjuang dengan masalah engagement dan turnover yang tak ada habisnya. Atau, kita bisa menerima umpan balik ini dengan rendah hati dan memulai perjalanan transformasi sejati.
Jadi, jika Anda melihat gejala-gejala quiet quitting di dalam tim Anda, jangan terburu-buru menyalahkan mereka. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang jujur: “Sudahkah saya menciptakan sebuah ‘taman’, bukan ‘pabrik’? Sudahkah saya menciptakan lingkungan di mana manusia bisa dan ingin bertumbuh seutuhnya?”
Jawabannya mungkin tidak nyaman, tetapi di dalam jawaban itulah terletak kunci untuk membangun organisasi yang tidak hanya produktif, tetapi juga hidup, bersemangat, dan menjadi rumah bagi talenta-talenta paling cemerlang di masa depan.